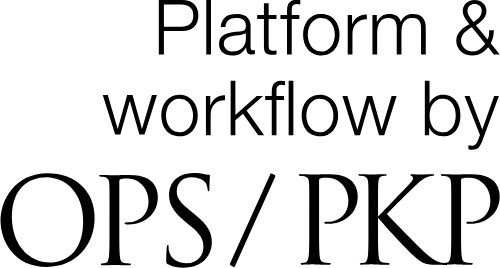Skripsi, tesis, dan disertasi terkunci di repositori universitas: minimnya akses karya ilmiah mahasiswa hambat iklim riset di Indonesia
 (Unsplash/Freestocks), CC BY
(Unsplash/Freestocks), CC BY
Luthfi T. Dzulfikar, The Conversation
Ilham Akhsanu Ridlo, dosen kesehatan masyarakat Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya, pada 2022 dihubungi rekannya, Grace Wangge, seorang dosen dan peneliti di Monash University Indonesia. Grace yang kala itu tengah melakukan kajian sistematis (systematic review) tentang kusta di Indonesia, meminta bantuan Ilham mengakses suatu tesis yang tersimpan di repositori (portal penyimpanan data akademik) Unair demi mendukung studinya.
Upaya Ilham membantu rekannya menemui jalan buntu. Dokumen versi lengkap dari tesis tersebut terkunci secara online, bahkan bagi dosen seperti Ilham.
Pihak perpustakaan menyarankan Grace datang langsung untuk membaca tesis tersebut secara fisik, tanpa bisa meminjam dan membawanya keluar perpustakaan kampus.
“Bayangkan, Mbak Grace di Jakarta, hanya untuk 1-2 artikel atau literatur harus ke Surabaya, yang setelah dibaca pun belum tentu artikelnya layak dimasukkan ke analisis,” kata Ilham.
Keterbatasan akses skripsi (S1), tesis (S2), dan disertasi (S3) mahasiswa yang terkunci di repositori universitas ini adalah kondisi umum di dunia perguruan tinggi Indonesia. Mayoritas repositori tertutup dan hanya bisa diakses warga kampus – itupun biasanya hanya sampai bab ‘metode’ dan tidak membuka bagian inti riset yakni bab ‘hasil dan pembahasan’.
Padahal, meski termasuk kategori ‘grey literature’ (literatur abu-abu), berbagai skripsi, tesis, dan disertasi bisa menjadi alternatif sumber data di tengah data riset yang terbatas di Indonesia.
Grey literature punya peran penting, tapi aksesnya minimKarya monograf – ditulis sendiri dan tidak melalui pengeditan atau telaah sejawat (peer review) – seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang tersimpan di repositori universitas, menduduki kasta terbawah dalam hierarki bukti akademik. Ia masih kalah dari artikel jurnal ilmiah.
Namun, Ilham mengatakan saat ini masih ada kelangkaan data dari artikel jurnal ilmiah di Indonesia, terutama pada bidang atau fokus riset tertentu.
“Menggali bukti terkait bidang khusus dalam ilmu kesehatan di Indonesia – misal epidemiologi obat, epidemiologi sosial, atau etnografi kesehatan – itu sulit. Artikel ilmiah saja banyak yang dibuat serampangan, proses penelaahannya banyak yang tidak layak, jurnalnya juga ada yang bagus ada yang enggak [..] Jadi sudah sedikit, hasilnya tidak begitu bagus lagi,” katanya.
Keterbatasan ini juga terkadang membuat Ilham dan peneliti lain gagal melakukan metaanalisis (kajian atas kompilasi data dari berbagai studi sebelumnya) karena kekurangan data atau riset kesehatan yang layak.
“Makanya untuk memperluas cakupan skrining bukti, kita juga butuh grey literature. Kalau riset dan mahasiswanya bagus, bisa jadi sarana bagi peneliti yang melakukan tinjauan pustaka, metaanalisis, atau kajian sistematis, atau untuk ringkasan kebijakan, misalnya,” ujar Ilham.
“Kalau repositori tutup, hanya mengandalkan artikel ilmiah dari jurnal, bagaimana [..] skripsi, tesis, atau disertasi itu bisa bermanfaat lebih?”
Gerakan repositori terbuka terhambat kebijakan publikasiFaizuddin Harliansyah, pustakawan akademik di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menceritakan beberapa perguruan tinggi sebenarnya sudah menjadi pionir repositori terbuka bahkan mulai tahun 2008-an.
Berkaca dari gerakan open access (akses terbuka) dan dengan dukungan masing-masing rektor, universitas seperti UIN Malang, UIN Walisongo, hingga Universitas Kristen Petra (UKP) menginisiasi repositori untuk menyimpan karya ilmiah mahasiswa yang bisa diakses publik.
“Dan ini teks penuh, bisa diakses siapapun, karena prinsip open access mensyaratkan kemudahan akses tanpa harus login, dan tidak parsial artinya yang dibuka keseluruhan riset, tidak hanya bab 1.”
Sayangnya, kata Faiz, terobosan open access ini kemudian “bertabrakan” dengan kebijakan pemerintah terkait publikasi karya mahasiswa selama satu dekade belakangan.
Keputusan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada 2012 – yang kemudian diperkuat berbagai peraturan menteri dan surat edaran lainnya – mewajibkan penerbitan skripsi, tesis, dan disertasi sebagai syarat kelulusan mahasiswa.
“Ketika kementerian memprioritaskan harus terbit dalam bentuk jurnal, pemahaman banyak kalangan jika [diunggah ke repositori] maka dianggap sudah terbit. Sehingga, [jika dipublikasikan lewat jurnal ilmah] akan dianggap duplikasi publikasi dan bahkan self-plagiarism (penjiplakan karya sendiri),” ujar Faiz.
Berkaca pada regulasi dan juga Panduan Editorial Pengelolaan Jurnal Ilmiah keluaran pemerintah, misalnya, pengelola jurnal wajib melakukan uji indeks kemiripan (similarity check) – misalnya dengan layanan deteksi Turnitin – dengan kemiripan maksimal 15%-25%.
Pada akhirnya, demi memfasilitasi kebijakan wajib publikasi ini, banyak repositori universitas terpaksa mengunci akses dokumen skripsi, tesis, dan disertasi agar tidak terdeteksi sistem pengecekan plagiasi.
Repositori UIN Malang, misalnya, pertama mulai menutup akses ke disertasi mahasiswa, lalu disusul beberapa skripsi dan tesis.
“Ini sudah dimulai dari jurusan-jurusan. Mereka memberikan surat kepada perpustakaan, memohon skripsi-disertasi jangan dibuka, karena masih proses submission (pengajuan) ke jurnal tertentu – itu banyak seperti itu.”
Riset tahun 2017 dari Liauw Toong Tjiek, peneliti di Universitas Kristen Petra (UKP), menemukan bahwa dari 52 sampel repositori universitas di Indonesia, hanya seperempat (26,9%) yang memberikan akses penuh untuk karya akademik mahasiswa – itu pun belum tentu seluruh jenis dokumen.
Angka ini berpotensi lebih rendah lagi seiring kebijakan kewajiban publikasi diadopsi dunia perguruan tinggi.
Berkaca dari tren open access globalFaiz menjelaskan bahwa Indonesia masih tertinggal dari banyak negara lain yang sudah menjadikan praktik open access sebagai norma akademik.
Ia mencatat beberapa perguruan tinggi di negara lain yang sukses membangun infrastruktur untuk menyebarluaskan tesis dan disertasi secara daring (e-thesis)
“Di University of Birmingham [platformnya] memuat e-thesis banyak, jadi khusus grey literature. Termasuk juga di Queensland University of Technology (QUT). Ini open access, mereka memandatkan. Semangat inilah yang dulu kami ikuti.”
Di level nasional, Perpustakaan Britania Raya bahkan mengindeks disertasi doktoral dari seluruh perguruan tinggi di Inggris – kini jumlahnya lebih dari 600.000 – dalam suatu repositori bernama E-Theses Online Service (EThOS).
Sementara di level global, ada Open Access Theses and Dissertations (OATD) yang mengkompilasi data lebih dari 1.100 perguruan tinggi. Menurut situs OATD, portal tersebut hingga kini telah mengindeks lebih dari 6 juta tesis dan disertasi.
Ilham dan Faiz menggarisbawahi kontrasnya filosofi akses repositori untuk skripsi, tesis, dan disertasi di tingkat global ini dengan di Indonesia.
“Mereka tidak memahami itu sebagai duplikasi, karena repositori fungsinya bukan untuk publikasi, tapi pengarsipan saja [..] yang kebetulan memang bisa diakses masyarakat luas. Itu pemahaman di sana” kata Faiz.
“Misalnya, jika draf yang aku submit ke jurnal ilmiah itu sama dengan misalnya preprint (manuskrip awal yang diunggah di suatu server akademik sebelum melalui peer review), itu nggak masalah. Tapi di Indonesia bisa jadi masalah, ‘lho kok mirip dengan repositori atau preprint ini’, banyak editor tidak bisa membedakan antara similarity dan plagiarisme,” ujar Ilham.
Jalan ke depanUntuk mengejar ketertinggalan ini, Faiz menekankan pentingnya kebijakan progresif dari berbagai pihak.
“Universitasnya iya, kementeriannya juga iya. Regulasi publikasi di level kementerian biasanya diikuti sekuat tenaga oleh universitas di bawahnya,” katanya.
Ia pun mendorong beragam asosiasi perpustakaan perguruan tinggi, advokat open acess, dan para pengelola jurnal ilmiah di Indonesia untuk lebih progresif memahami perbedaan konsep similarity, plagiasi, dan duplikasi.
Harapannya, publikasi via jurnal maupun diseminasi karya mahasiswa, dua-duanya bisa berjalan sebagai pilar penting komunikasi ilmiah.
Selain itu, menurut Ilham, banyak dosen dan pimpinan perguruan tinggi juga waswas jika repositori terbuka. Mereka takut bahwa berbagai praktik akademik yang buruk yang terjadi selama ini akan lebih mudah terkuak – dari karya ilmiah mahasiswa yang merupakan hasil plagiasi maupun berujung diplagiasi, hingga kualitas pembimbingan skripsi yang buruk.
“Kalau kita mau berpikir solutif, kita nggak usah berpikir mundur, ya sudah lah yang di belakang ini. Kita mikir saja ke depan gimana,” katanya.
“Kalau nanti nggak ada jalan tengah ini, ya selamanya akan tertutup terus. [Repositori yang terbuka] malah akan membangun kultur akademik yang bagus karena semakin terbuka justru menekan praktik plagiarisme.”
Luthfi T. Dzulfikar, Youth + Education Editor, The Conversation
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.